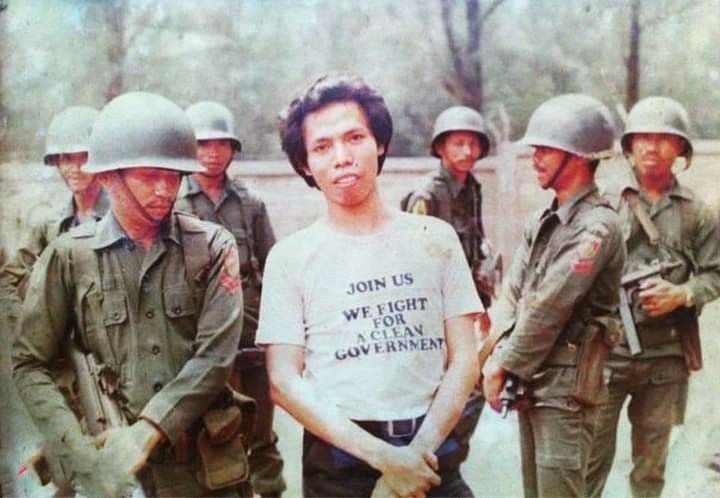Oleh
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
(Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
|
M
|
 asyarakat adat dengan segala hak-hak tradisionalnya, khususnya terhadap sumberdaya alam sesungguhnya telah memperoleh pengakuan, baik pada level nasional maupun internasional. Pada level internasional, berbagai konvensi telah mengukuhkan kedudukannya tersebut, antara lain Konvensi ILO No. 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (Concerning Indigenous and Tribunal People in Independent State), menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan niulai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan. Dalam konteks nasional, pengakuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam konstitusi negara UUD NRI 1945, Pasal 18B ayat (2), bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu, Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pasal 5 huruf “j” juga menegaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam.”
asyarakat adat dengan segala hak-hak tradisionalnya, khususnya terhadap sumberdaya alam sesungguhnya telah memperoleh pengakuan, baik pada level nasional maupun internasional. Pada level internasional, berbagai konvensi telah mengukuhkan kedudukannya tersebut, antara lain Konvensi ILO No. 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (Concerning Indigenous and Tribunal People in Independent State), menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan niulai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan. Dalam konteks nasional, pengakuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam konstitusi negara UUD NRI 1945, Pasal 18B ayat (2), bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu, Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pasal 5 huruf “j” juga menegaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam.” Namun demikian, jika dicermati lebih dalam ternyata pengakuan kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya oleh Negara masih sebatas pengakuan yuridis-normatif yang kelihatannya sulit untuk diwujudkan karena adanya beberapa syarat yang mengikutinya, yaitu: (a) sepanjang masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) prinsip NKRI; dan (d) diatur dalam undang-undang. Segenap persyaratan tersebut masih membutuhkan penjabaran dan penegasan lebih lanjut, agar dapat diperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut.
Pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut tentunya harus diikuti dengan pemberian hak eksklusif kepada masyarakat untuk menguasai dan mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya, seperti tanah, hutan dan wilayah perairan tertentu yang memang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat adat (lebensraum) mereka.
Dalam pandangan masyarakat adat, bahwa hubungan manusia dengan alam di sekitarnya adalah hubungan religio-magis yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada umumnya komunitas masyarakat adat memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni di antara keduanya. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan hutannya maka pada umumnya telah mengembangkan konsep kepemilikan (property rights) secara komunal dan bersifat eksklusif atas suatu kawasan hutan adat. Contoh yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah pengembangan sistem kepemilikan atas tanah dan hutan yang ada di wilayah masyarakat hukum adat “Ammatowa” di Kabupaten Bulukumba, dimana penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan di kawasan tersebut diatur dan dipimpin oleh Ammatowa. Pola pengaturan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya bersumber pada Hukum Adat yang merupakan pranata sosial yang paling penting bagi masyarakat untuk mengamankan sumberdaya di dalam kawasan atau wilayah mereka dari penggunaan berlebihan baik oleh anggota masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar.
Konsepsi Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum
Secara konseptual, istilah masyarakat adat sesungguhnya berbeda dengan masyarakat hukum adat. Kajian akademis dari beberapa pakar telah memberikan dasar teoretis latar belakang penggunaan kedua istilah tersebut. Istilah “masyarakat adat” diambil dari terjemahan kata “indigenous peoples”, sedangkan istilah “masyarakat hukum adat” merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “rechtsgemenschap”. Istilah “rechtsgemenschap” tersebut adalah istilah yang dihubungkan dengan istilah “adatrecht” yang dipopulerkan Cornellis Van Vollenhoven dalam bukunya Het Adatrecht van Netherland Indie.1
Pendapat tersebut memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap istilah masyarakat adat bila dibandingkan dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat adat diyakini memiliki dimensi makna yang luas dari sekadar aspek hukum, sebab dalam masyarakat adat sangat erat terkait dengan dimensi kultural, religi, dan sebagainya. Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan pada bulan Maret 1999, disepakati bahwa “masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”.
Sementara Konvensi ILO No. 169 Tahun 1999 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (Concerning Indigenous and Tribunal People in Independent State) mengartikan “indigenous peoples” sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di Negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-ku bangsa yang telah mendiami sebuah Negara sejak masa kolonial yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.
F.D. Hollemann dalam bukunya “De Commune Treck in het Indonesische Rechtsleven”2 mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Keempat sifat tersebut dapat dideskrepsikan sebagai berikut. (1) Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang pralogika, animism dan kepercayaan pada alam gaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama, religiusitas diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan YME. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai derajat perbuatannya. (2) Sifat komunal (commuun), yaitu masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu anggota
masyarakat merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. (3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. (4) Sifat kontan (kontante bandeling) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Artinya setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan sertamerta/seketika.
Sementara itu, walaupun para ahli menganggap istilah masyarakat hukum adat hanya akan mempersempit entitas masyarakat adat sebatas pada entitas hukum, tetapi secara yuridis-normatif istilah masyarakat hukum adat-lah yang lebih tepat jika dikaitkan dengan eksistensi dari masyarakat adat itu sendiri beserta hak-haknya, karena eksistensi dan hak-hak tersebut justru ada dalam masyarakat hukum adat yang diatur oleh hukum adat itu sendiri. Demikian halnya jika ditelusuri berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UUD NRI 1945, justru istilah “masyarakat hukum adat”-lah yang digunakan. Pengertian dari masyarakat hukum adat oleh beberapa pakar, antara lain diberikan oleh Kusumadi Pujosewojo3, bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Kusumadi membedakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum yang diartikan sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri.
Ter Haar4 memberikan pengertian masyarakat hukum adat sebagai kelompok manusia yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri, baik berwujud (benda) maupun tidak berwujud (immaterial), dimana para anggota kelompok masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota tersebut mempunyai pikiran untuk membubarkannya, atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Di situlah terdapat hukum adat sebagai endapan dari kekayaan social yang didukung dan dipelihara oleh dan keputusan pemegang kekuasaan atau penghulu rakyat dan rapat yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau suatu perselisihan (beslissingen).
Sedangkan menurut Wignjodipuro dalam Farida Patittingi5, masyarakat hukum adat (persekutuan hukum adat) adalah kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan immaterial. Masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat terbentuk karena adanya pertalian darah/keturunan (genealogis), adanya kesamaan daerah tempat tinggal (terotorial), serta percampuran keduanya (genealogis-territorial).
Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri dari suatu masyarakat hukum adat (adatrechtsgemenschap), yaitu: (1) adanya kesatuan manusia yang teratur; (2) menetap di suatu daerah tertentu; (3) mempunyai penguasa-penguasa; (4) mempunyai kekayaan, baik kekayaan materiil (berwujud) maupun yang immaterial (tidak berwujud); (5) memiliki sistem nilai dan kepercayaan; serta (6) memiliki tatanan hukum sendiri.
Secara konsepsional sebagaimana telah diuraikan di atas, suatu masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat apabila masih memiliki ciri-ciri sebagaimana telah dikemukakan oleh para pakar hukum Adat tersebut di atas. Namun demikian, dalam konteks kebijakan hukum (legal policy), segenap ciri-ciri tersebut harus dikukuhkan dalam suatu peraturan hukum, agar dapat menjadi acuan yang bersifat umum untuk menentukan keberadaan dari suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut membawa konsekuensi terhadap hak-haknya atas sumberdaya alam yang ada di wilayahnya serta pernyataan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengelola sendiri sumberdaya yang ada di wilayahnya tersebut.
Dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum adat tersebut dirumuskan sebagai hak yang bersifat komunalistik religious. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas suatu sumberdaya (khususnya tanah dan tanaman-tanaman yang ada di atasnya) yang dalam kepustakaan Hukum Adat disebut Hak Ulayat. Hak Ulayat adalah hak bersama masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai karunia sesuatu Kekuatan Ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.
Sumberdaya milik bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan suatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Dalam konteks kepentingan inilah maka masyarakat hukum adat dibebani kewajiban untuk mengelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama.
Peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu diatur oleh kelompok yang bersangkutan, supaya selain dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindarkan sengketa, juga bisa terjadi kelestarian kemampuannya bagai generasi yang akan datang. Inilah yang merupakan konsep pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan dari masyarakat Hukum Adat. Menjaga alam lingkungannya adalah menjaga kehidupannya itu sendiri, sebaliknya menghancurkan alam lingkungannya berarti menghancurkan kehidupannya itu sendiri.
Dengan demikian, dalam konsep Hak Ulayat masyarakat hukum adat terdapat 2 (dua) konsep hukum, yaitu unsur kepunyaan bersama atas tanah bersama beserta tanaman yang ada di atasnya yang termasuk dalam bidang hukum perdata, dan sekaligus mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk dalam bidang hukum publik.
Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama, baik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun bagi kepentingan para warganya, tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, maka sebagian tugas tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Adat sendiri bersama Tetua Adat.
Dalam konsep Hukum Adat, pelimpahan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik itu tidak meliputi atau tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah bersama yang beraspek hukum perdata. Hak kepunyaan atas tanah bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang berarti tetap ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada Kepala Adat. Hak bersama tersebut bukan hak milik dalam arti yuridis, melainkan hak kepunyaan bersama.
Secara konseptual menurut Hukum Adat sebagaimana diuraikan di atas, hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya alam (khususnya tanah dan hutan) tidak hanya mengandung unsur kepunyaan, tetapi juga tugas kewajiban mengelola. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, perlu dukungan kebijakan hukum (legal policy) dari Pemerintah agar perlindungan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta beserta hak-hak tradisionalnya memperoleh kepastian hukum.
Hal ini penting, sebab berbagai analisis pakar maupun masyarakat secara luas melihat bahwa pengakuan yang diberikan oleh Negara terhadap keberadaan atau eksistensi masyarakat hukum adat dalam tataran peraturan perundang-undangan masih dianggap sebatas pengakuan secara yuridis-normatif, yang sulit dituntut pemenuhannya oleh masyarakat hukum adat itu sendiri atau pihak-pihak yang terkait. Anggapan demikian karena adanya beberapa persyaratan yang ketat yang menyertai pengakuan tersebut. Seperti pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 atau pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 UUPA masih membutuhkan kejelasan atas persyaratan yang mengikutinya.
Misalnya Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Syarat yang mengikutinya ada 2 (dua) yaitu (a) eksistensinya, artinya sepanjang dalam kenyataannya masih ada; dan (b) pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan kepentingan nasonal dan Negara dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Segenap persyaratan tersebut masih membutuhkan kejelasan dan kesepakatan hukum agar dapat menjadi pedoman bersama antara Pemerintah yang mewakili kepentingan Negara dengan masyarakat hukum adat yang membutuhkan perlindungan dalam penegakan hak-hak mereka. Hal ini penting sebab pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonlanya dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini masih sulit untuk dituntut pemenuhannya oleh masyarakat hukum adat, akibat ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi yang justru cenderung melemahkan kedudukan masyarakat hukum adat itu sendiri.
Semoga ke depan, negara secara konsisten dapat memberikan pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tersebut, dengan memberikan kejelasan atas semua syarat yang ketat tersebut, agar amanat konstitusi untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat dapat terwujud. Oleh karea itu, maka kehadiran Undang-Undang tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya menjadi sebuah keniscayaan. Kita tunggu saja.
1 Dalam Husen Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak MAsyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Mendatang), Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal. 80.
2 Dalam Otje Salman S, 2002, Rekonstruksi Hukum Adat Kontemporer, Penerbit PT.Alumni, Bandung, hlm. 29-30.
3 Dalam Maria S.W.Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 56
4 Ter Haar, 2001, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan K.Ng.Soebakti Poespono). Cetakan ke-13, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 28
5 Farida Patittingi, 2009, Kebijakan Pengaturan Tanah Pulau- Pulau Kecil, Penerbit Lanarka, Yogyakarta, hlm. 124-125.