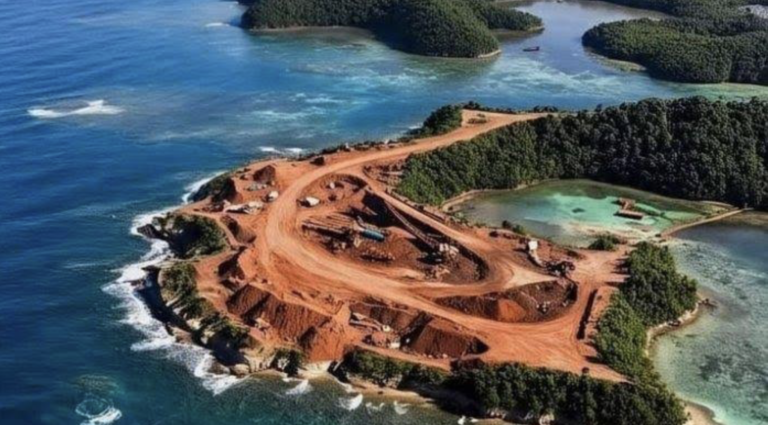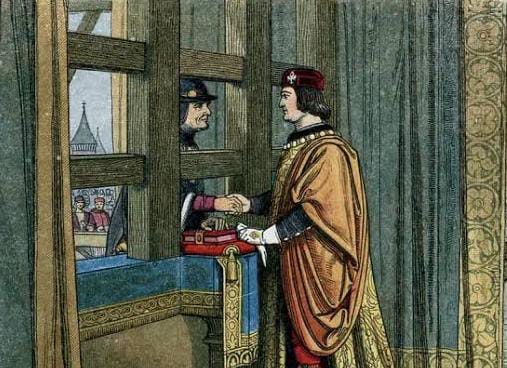Ramli
Pengurus LPMH-UH Periode 2014-2015
Tepat tanggal 11 Juni 2014, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi diberlakukan. Aturan tersebut tak pelak menuai penolakan karena pada Pasal 17, memuat pembatasan masa kuliah untuk program studi Strata I (S1). Untuk mendapat gelar sarjana, mahasiswa wajib melulusi 144 Satuan Kredit Semester (SKS) dengan masa studi terpakai adalah 5 tahun.
Ditakutkan, aturan tersebut akan memaksa mahasiswa hanya fokus pada persolan akademiknya, sehingga melupakan fungsi sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. Sejalan dengan itu, realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa jadi pincang. Hanya aspek pendidikan yang akan terpenuhi, sedangkan tangggung jawab perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat akan terbengkalai.
Bukan dugaan tanpa alasan jika mahasiswa akan tak acuh terhadap fenomena sosial jika masa kuliah dibatasi 5 tahun. Mahassiwa terpaksa terpaku pada kegiatan kurikuler agar dapat lulus, atau jika tidak, akan terancam drop out (DO). Aturan ini jelas tidak mempertimbangkan keaktifan mahasiswa pada kegiatan ektrakurikuler. Padahal fakta menunjukkan kualitas kepribadian mahasiswa sangat terdampak dari proses di organisasi kemahasiswaan. Hal ini tentu berdampak juga bagi mahasiswa dalam menghadapi kenyatan dunia kerja.
Memaksa Mahasiswa “Membisu”
Sekali lagi, secara matematis, tidak salah jika mahasiswa diproyeksikan melulusi 144 SKS dalam rentang lima tahun. Tapi dampaknya, akan membuat mahasiswa melalaikan fungsi sosialnya karena waktunya terkuras untuk aktivitas perkuliahan. Pada asal 16 ayat (1) Permendikbud No. 49/2014 jelas diuraikan bahwa 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah mencakup: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Jadi akumulasi waktu untuk 1 SKS adalah 160 menit. Dengan begitu, selepas kuliah di kelas, mahasiswa akan kembali disibukkan dengan tugas kuliah yang menumpuk.
Anggapan pemerintah bahwa mahasiswa dapat melulusi 144 SKS dalam 5 tahun menjadi alasan kuat pembatasan masa kuliah dalam Permendikbud No. 49/2014. Perkiraan tersebut diakui mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh yang menandatangani Permendikbud tersebut. Mangacu pada Pasal 17 ayat (1), beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu, setara dengan 18 sks per semester (48 jam x 60 menit : 160 menit/SKS=18 SKS). Bisa juga sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam per minggu, setara dengan 20 sks per semester. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyelesaikan beban 144 SKS dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Bahkan Pasal 17 ayat (4) membolehkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama untuk menambah hingga 64 jam per minggu, setara dengan 24 SKS per semester. Dengan demikian, mahasiswa bahkan dapat melulusi 144 SKS dalam waktu 3.5 tahun atau 7 semester.
Estimasi di atas tidaklah salah. Namun kungkungan batasan masa kuliah di saat aktivitas mahasiswa tidak hanya kuliah, tetapi juga berorganisasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, rentan membuat mahasiswa kelabakan. Terlebih tanggung jawab sebagai pengurus organisasi biasanya menjadi pertimbangan khusus mahasiswa untuk tidak memprogram jumlah SKS maksimal per semester. Pertimbangan tersebut tidak melulu didasarkan kemalasan atau ketidakmampuan mahasiswa me-manage waktunya, tetapi juga pertimbangan logis untuk memperoleh manfaat kuliah dan organisasi secara maksimal. Jika beban SKS dipaksakan, bisa jadi mahasiswa akhirnya asal lulus. Sekali lagi, organisasi sangat menentukan dalam pembentukan karakter mahasiswa.
Mengabaikan Kualitas Lulusan
Keinginan pemerintah agar kuota bangku kuliah yang katanya terbatas, dienyam oleh sebanyak mungkin lulusan sekolah menengah, juga menjadi alasan kuat pembatasan masa kuliah. Dengan begitu, diharapkan mahasiswa cepat lulus dan kursi yang kosong akan diisi angkatan baru. Alasan ini jelas terkesan hanya memfokuskan perhatian pada persoalan kuantitas lulusan. Kualitas lulusan pun tidak jadi prioritas dengan adanya pengekangan waktu.
Kualitas lulusan tidak seharusnya ditumpukan sebatas penguasaan materi perkuliahan, tetapi berorientasi pada kebutuhan pembangunan bangsa dan negara. Fenomena kebangsaan membuktikan Indonesia tidak membutuhkan orang pintar, tapi yang berkarakter pemimpin. Ini tentu juga sesuai tujuan pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun teknis pada Permendikbud 49/2014 malah tak mendukung. Kakunya suasana kuliah dipastikan tidak akan membentuk karakter mahasiswa, kecuali mengasah aspek intelektual semata. Pembentukan aspek emosional mahasiwa sebagai bakal pemimpin efektif melalui organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa yang dicitakan adalah bertangsung jawab, menghargai pendapat orang lain, komunikatif, mudah bergaul, demokratis, dan lain-lain.
Kualitas akan semakin dikesampingkan jika melihat kultur dalam institusi pendidikan yang gemar mengejar predikat. Tidak hanya pada tingkat institusi pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga perguruan tinggi. “Permainan” internal sering dilakukan untuk menjaga citra institusi demi mendapatkan predikat terbaik, misalnya melalui penilaian akreditasi. Jalannya tidak lain dengan mempermainan unsur penilaian. Wujudnya dapat dengan asal memberikan nilai tinggi kepada mahasiswa dengan melanggar prinsip objektivitas. Termasuk juga mengusahakan semua mahasiswa lulus dengan nilai tinggi dan tanpa DO agar institusinya dianggap berhasil.
Terkait kuota bangku di perguruan tinggi yang dinilai tidak mampu menampung tamatan sekolah menengah, seharusnya disikapi pemerintah dengan memperbaiki dan menambah prasarana pendidikan tinggi, melakukan pemerataan ketersediaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, hinggga mendirikan perguran tinggi baru. Harus juga dicatat bahwa persoalan ekonomi merupakan salah satu penyebab banyaknya orang tak melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Selain itu, terdapat juga sejumlah perguruan tinggi yang malah kesulitan mencari calon mahasiswa karena institusinya dinilai tak berkualitas ataukah tak bergengsi.
Menciptakan Pengangguran
Era globalisasi telah menimbulkan keterpengaruhan antar bangsa, termasuk dalam persaingan kerja. Menjelang ASEAN Economy Community 2015, dibutuhkan sarjana berdaya saing tinggi, bukan sekadar mencetak lulusan berijazah. Persaingan kerja dewasa ini butuh keterampilan individu. Persaingan kerja akan dimenangkan orang yang punya kemampuan personal. Apalagi dunia kerja yang digeluti kadang tidak ada relevansinya dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Fakta membuktikan bahwa softskill seseorang sangat menentukan keberhasilan dalam persaingan kerja. Di satu sisi, teori dari bangku kuliah hanya akan menumpuk, lalu hilang sedikit demi sedikit di memori kita.
Pembatasan masa kuliah untuk melahirkan sebanyak mungkin sarjana sangat mungkin melahirkan sarjana pengangguran. Kuantitas tanpa dibarengi kualitas hanya akan melahirkan mahasiwa “robot” yang menunggu dipekerjakan. Keadaan diperparah jika sarjana yang seharusnya memiliki kemampuan analisis, tidak kreatif berinovasi dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Buktinya, banyak sarjana rela menganggur dan menunggu demi menjadi pegawai negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir di Koran Tempo (12/11/2014), tenaga kerja Indonesia per Agustus 2014 mencapai 182,99 juta orang. Sementara tingkat pengangguran terbuka (tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan) mencapai 5,94% dari jumlah penduduk, atau 7,24 juta orang. Dari jumlah pengangguran tersebut, total sarjana pengangguran mencapai 5,65%, naik dari Agustus 2013 sebesar 5,39%.
Ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja atau setidaknya memberikan sokongan dan stimulus bagi bakal pengusaha pencipta lapangan kerja, menambah runyam keadaan. Akibatnya, lapangan kerja yang stagnan tidak mampu menampung lulusan yang semakin membludak nantinya. Tidak terelakkan lagi bahwa akan lahir pecundang-pecundang baru yang hanya terdiam menunggu kapan waktunya “robot-robot tua” siap digantikannya.
Sikap: Perlu Bijak
Munculnya penolakan aturan batasan kuliah 5 tahun tidak terelakkan, terutama dari pihak disiplin ilmu sarat praktikum yang memiliki kajian keilmuan rumit dan menguras waktu. Penolakan juga berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) yang menilai standar mahasiswanya tidak dapat disamakan dengan mahasiswa perguruan tinggi negeri yang telah melalui tahap seleksi ketat. Selain itu, tidak memadainya sarana dan prasarana kampus PTS karena tidak disokong pemerintah ditakutkan tak dapat mengoptimalkan proses pembelajaran.
Waktu seharusnya tidak perlu menjadi patokan penciptaan sarjana, apalagi setiap orang tidak bisa disamakan dalam kemampuannya melulusi dan memahami sajian mata kuliah. Untuk itu, masa kuliah 7 tahun selama ini sudah ideal. Batasan masa kuliah 5 tahun hanya akan menekan mahasiswa karena terkesan memandang tugas mahasiswa sekadar kuliah di kelas. Imlikasinya, semakin banyak mahasiswa gagal menjadi sarjana hanya karena melampaui batas waktu, padahal ia punya tujuan mulia untuk mengembangkan dirinya dan terdidik di perguruan tinggi.
Kewajiban pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan permendikbud tersebut paling lambat 2 (dua) tahun, kiranya dapat menjadi rentang waktu untuk berpikir matang-matang terkait pemberlakuannya. Kebijakan pembatasan masa kuliah 5 tahun dapat saja menjadi aturan yang seharusnya diterima jika ada jaminan bahwa mahasiswa akan diperlakukan dan akan berkelakuan sebagai mahasiswa sejati. Namun besar dugaan penulis, batasan itu hanya akan melahirkan “robot-robot baru”.