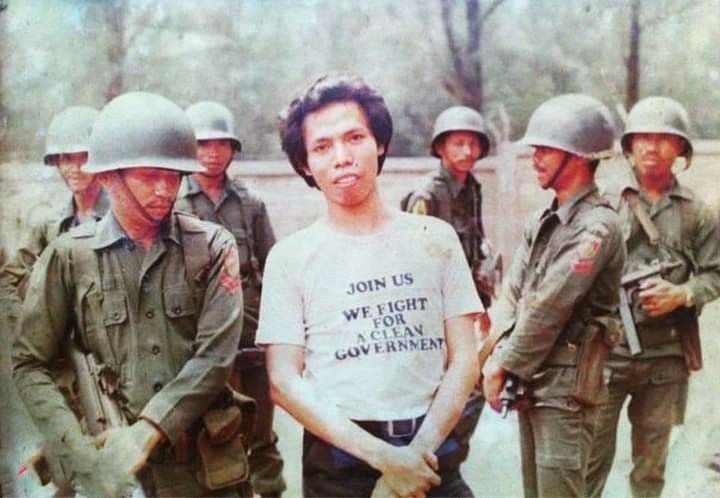Abdul Munif A
(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2017)
Kita akan sering mendengar celoteh “Katanya benci kapitalisme, tetapi masih saja menggunakan handphone.” Ya! Kalimat tersebut merupakan apa yang common logic telah konstruksikan. Sebuah kependekan sumbu berpikir. Lantas, apakah kapitalisme memang hanya sebatas Samsung? Apple? Nike? hingga Indomie ataupun sabun Lifebuoy?
Perlu ditegaskan kembali bahwa untuk mendeskripsikan kapitalisme tidaklah sesederhana itu. Bukan berarti saya beritikad akan pendeskripsian kapitalisme semakin rumit, tetapi untuk memahaminya kita memang perlu keluar dari kemandulan berpikir itu. Samsung, Apple, Nike, hingga Indomie ataupun Lifebuoy merupakan merk dari komoditas tertentu. Sudah nyata adanya bahwa komoditas merupakan salah satu bagian terpenting dalam kapitalisme, tetapi bukan berarti ia adalah dapat dijadikan pengertian yang bersifat final.
Pendeskripsian akan kapitalisme sendiri jauh melampaui apa yang common logic konstruksikan layaknya celoteh di atas. Kapitalisme, sedari awal, merupakan suatu corak produksi (mode of production) dalam masyarakat. Corak produksi terdiri dari jalinan relasi sosial, pengorganisasian produksi, dan bagaimana hasil produksi itu didistribusikan antar kelas-kelas sosial yang ada. Berdasarkan pengertian corak produksi tersebut, maka kapitalisme itu merupakan jalinan relasi sosial upah-mengupah, suatu pengorganisasian produksi berdasarkan kepemilikan akan sarana-sarana produksi (modal, tanah, pabrik, mesin, dan lainnya) oleh seseorang ataupun segelintir orang, dan distribusi hasil produksi untuk ditukarkan dalam mekanisme pasar, yang ditujukan guna menumpuk laba.
Sederhananya, sejauh ini saya menggarisbawahi bahwa kapitalisme merupakan tatanan masyarakat yang dilandaskan akan relasi upah-mengupah yang dalam artian lain merupakan relasi jual-beli.
Tiga ciri dari kapitalisme yang cukup netral dan dapat diterima menurut Simon Tormey adalah sebagai berikut: [1]
- Adanya kerja upahan atau pekerja yang diupah oleh pihak pengupah
- Kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi
- Produksi komoditas guna pertukaran melalui mekanisme pasar dan untuk mengeruk keuntungan berlipatganda
Kapitalisme dengan ketiga ciri mendasarnya di atas menegaskan kembali akan wataknya yang sangat eksploitatif dan otoritarian. Telah menjadi hal yang pasti, kekayaan yang terus mengalir ke seseorang ataupun segelintir orang. Berjalannya roda peradaban dan seluruh produksi kekayaan material adalah curahan kerja dari kelas pekerja yang juga berarti penumpukan nilai-lebih dari setiap kerjanya.[2]
Sekilas dari penggambaran kapitalisme di atas, sebagaimana common logic melihat segala sesuatu secara hitam-putih atau baik-buruk, lantas apa yang salah dengan sistem seperti itu? Mungkin terlalu banyak yang akan diidentifikasikan kebobrokan dari sistem ini. Namun setidak-tidaknya, saya sendiri mengidentifikasinya dengan rentetan argumentasi sebagai berikut:
- Kelas sosial dan Relasi sosial upah-mengupah dalam masyarakat
Apa itu kelas sosial? Ia merupakan keterpilahan ataupun penggolongan masyarakat dalam unit-unit tertentu berdasarkan kedudukan dalam hierarki sosial. Secara sederhana, dalam kapitalisme ada pihak yang memberikan upah dan yang diupah. Pihak yang mengupah dalam artian ini yang Marx jelaskan adalah Borjuis. Borjuis sendiri adalah puncak hierarki dalam masyarakat. Ia adalah pemodal. Begitupun dengan proletariat, pihak yang diupah. Proletariat merupakan kelas sosial dalam masyarakat yang tidak memiliki kontrol penuh akan hidupnya, yang dimana ia harus berhadapan pada suatu pilihan: menjual tenaga kerjanya kepada Borjuis untuk mendapatkan upah. Ataupun berhadapan pada pilihan-pilihan lain: mati kelaparan sebagai pengangguran, menjadi pengemis, pencuri atau perampok, lari ke hutan, bunuh diri, atau mengorganisir diri untuk perjuangan menuju tatanan masyarakat yang lebih baik (yeah!).
Dengan penjabaran ini, tentu sangat bertolak dengan common logic. Saya dapat membayangkan seseorang akan mengatakan “bukankah mereka menjadi buruh sebab mereka tidak mengenyam pendidikan dengan baik? Ataupun mereka adalah orang-orang yang tidak bersekolah? Jikapun mereka dapat menjalankan pendidikannya dengan baik, pasti mereka tidak bernasib seperti itu” kepada saya. Sebuah celoteh yang paling menyebalkan. Ya! Masyarakat kapitalis pun telah merekonstuksi orientasi serta tujuan dari pendidikan itu sendiri hanya untuk sebatas bekerja! Bagaimana menjadi sukses, kaya-raya, pun atau masuk surga (upss…). Sebagaimana menurut Marx, dominasi kelas borjuis telah mengubah fisikawan, pengacara, pendeta, ilmuwan, dan lainnya sebagai buruh upahan[3]. Yang jika dijabarkan lebih lanjut, menjebak setiap orang dalam relasi upah-mengupah. Namun poin pentingnya bukanlah menyoal kebodohan ataupun bukan berpendidikannya kelas buruh, yang menentukan “takdir dari Tuhan” mereka, melainkan mengapa buruh itu ada.
Sederhanya, kelas proletariat (buruh, kaum miskin, dan lainnya) ada karena adanya ketimpangan sosial. Mengikuti alur historis, proletariat sendiri ada tentu karena adanya segelintir orang yang merampas, mencuri, merampok, menguasai, memiliki, ataupun mengontrol sarana produksi berupa tanah dan sumber daya beserta perkembangan mutakhir alat-alat produksi. Ekonom liberal-klasik Adam Smith menganggap asal-usul ketimpangan tersebut berdasar atas adanya orang-orang yang rajin, hemat, serta kreatif, dan di sisi lain merupakan orag-orang malas, boros, dan bodoh. Tentu, anggapan Adam Smith adalah bagian dari Common Logic, bahwa adanya kaya dan miskin itu sesuatu yang sedemikian adanya. Berbeda dengan Marx yang menjelaskan asal-usul ketimpangan sosial berasal bukan dari sesuatu yang alamiah, melainkan karena adanya perampasan tanah, pengkaplingan, pengusiran kaum tani, kebijakan upah murah, dan sebagainya yang mendasari adanya kelas-kelas sosial.[4] Hal inilah yang disebut sebagai akumulasi primitif sekaligus proletarisasi.
- Ketiadaan kontrol akan hidup atau keniscayaan mutlak berhadapan dengan dunia kerja yang eksploitatif
Yang membedakan buruh upahan dengan budak adalah adanya kebebasan tertentu yang dimiliki oleh buruh (ini merupakan spekulasi borjuis), sedangkan budak sama sekali tidak memilikinya. Bebas dalam artian buruh berkeinginan untuk bekerja tanpa adanya keterpaksaan terhadap siapa ia akan bekerja, yang membedakan ia dengan budak yang diperjualbelikan dan dimiliki oleh tuannya. Namun makna pekerja “bebas” yang melekat pada buruh adalah sesuatu yang nihil. Bahkan jika menggunakan kacamata hukum, secara yuridis-teknis buruh memang bebas tetapi yuridis-sosiologis ia sama sekali tidak bebas[4]. Sebab, buruh sendiri tidak memiliki pilihan lain selain menjual tenaga kerjanya demi mendapatkan upah, terlepas kepada tuan mana yang ia berkehendak untuk bekerja.
Tenaga kerja atau yang merupakan kapasitas berupa keterampilan dan kognisi manusia telah berubah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan. Manusia dalam masyarakat kapitalis menjual aktivitas hidupnya dengan upah yang ditawarkan oleh kapitalis[5]. Hidup dalam masyarakat kapitalis sama dengan hidup yang ditaksir dengan upah sekaligus terkurung dalam delapan jam kerja (ataupun lebih) per hari. Ritme hidup yang monoton dan keterasingan manusia adalah kenyataan pelik yang tak dapat dielakkan. Dengan begitu, kapitalisme merupakan perbudakan modern yang sangat halus, sistematis, serta berwajah manusiawi dengan atribut kebebasan yang palsu.
Ada lagi satu celoteh: “bukan kah justru penanaman investasi sama dengan penciptaan lapangan pekerjaan? Sehingga permasalahan pengangguran dapat diselesaikan?”. Namun sayangnya, pengangguran pun tetap dipelihara kuantitasnya guna mengendalikan harga upah. Semakin banyak pengangguran berarti semakin murah lah suatu upah, dan semakin berkurang pengangguran berarti semakin mahal pula suatu upah.
- Ketergantungan global
Di bawah kapitalisme, kita akan mendapati diri kita menderita krisis ekonomi global, kerusakan alam akibat akumulasi kapital, liberalisasi pendidikan yang kemudian membuat kita menanggung biaya kuliah tinggi (jangan bohong, UKT 5 mahal kan?), upah murah negara-negara dunia ketiga, bahkan suatu keharusan menjadi warga negara yang baik dengan memikul tanggung jawab utang luar negeri triliunan warisan Soeharto hingga Jokowi.
Sebagai negara dunia ketiga, dengan biaya hidup yang begitu rendah, Indonesia telah menjadi sasaran-sasaran ekspansi (perluasan) kapital transnasional. Biaya hidup rendah berarti upah semakin murah, sebab biaya hidup merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur taksiran upah[6]. Toh, jika upah pun semakin murah itu juga berarti keuntungan atau laba dapat ditumpuk dan semakin berlipat ganda.
Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan transnasional seperti Coca-Cola, McDonald, Nike, Samsung, Uniliver, Citibank dan lainnya kian menjamur di mana-mana. Perluasan kapital-kapital tersebut tidak lain memiliki suatu tujuan saja: Penumpukan laba di mana-mana. Kapitalisme, dengan demikian, sama sekali tidak mengenal konsep kebangsaan.[7]
Berdasarkan uraian di atas, tentu tidak dapat merangkum bagaimana kapitalisme secara sistematis bekerja keseluruhan. Namun untuk keluar dari rekonstruksi common logic, ini merupakan satu dari banyak upaya untuknya. Kapitalisme memungkinkan hidup kita ditaksir dengan upah, terkurung dalam penjara jam kerja, menjadikan kita maupun penerus kita sebagai cadangan tenaga kerja di masa depan, memungkinkan kita menderita krisis ekonomi global dan jeratan utang luar negeri, memungkinkan pendidikan terkapitalisasi, memungkinkan kerusakan alam akibat eksploitasi demi penumpukan laba, memungkinkan ruang-ruang hidup dirampas dan digantikan pusat-pusat perbelanjaan, pabrik, perumahan, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Dengan demikian, maka tak ada lagi bagi kita kemungkinan untuk tidak membencinya. Kapitalisme harus dibenci!
Catatan Kaki
[1] Simon Tormey. “Anti-Kapitalisme: Panduan Bagi Pemula”. (Penerbit Angin, 2016). Hlm. 14.
[2] Dalam penjabarannya pada jilid III Das Kapital, Marx menjelaskan bahwa nilai-lebih merupakan kelebihan nilai komoditas di atas harga pokoknya. Yang lebih lanjut sebagai lebihan jumlah total kerja yang terkandung dalam komoditas melebihi jumlah kerja yang telah sungguh-sungguh dibayar. Singkatnya, nilai-lebih adalah kenyataan bahwa kapitalis memiliki sesuatu yang tak ia bayarkan kepada buruh. Nilai lebih merupakan sinonim dari laba.
[3] Marx & Engels. “Manifesto of Communist Party”.
[4] Dede Mulyanto. “Genealogi Kapitalisme”. (Yogyakarta: Resist Book, 2012). Hlm. 42-44
[5] A Ilyas. “Hukum Perburuhan”. (Rangkang Education, 2009).
[6] Jurnal Kontinum Vol.2 2008.
[7] Simon Tormey. Op.Cit., 27.
[8] Ibid. Hlm. 28.