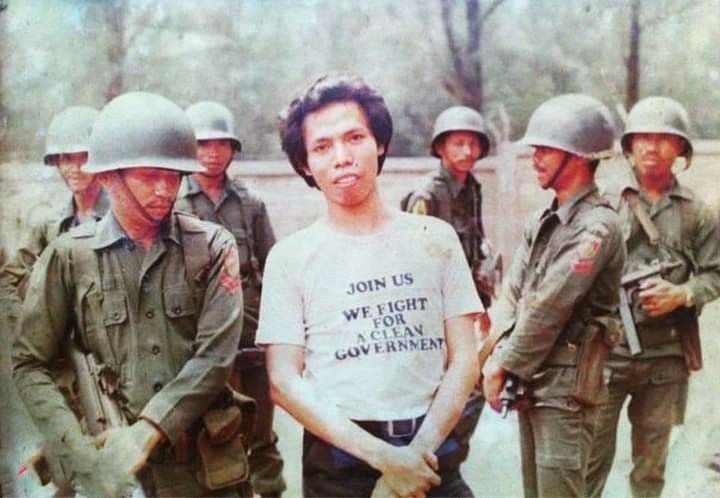Musthakim Algozaly
(Ketua Umum Garda Tipikor FH-UH periode 2016-2017)
Manisfestasi motif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mereduksi pemberantasan korupsi sangat terdeteksi memasuki triwulan pertama kalender 2017. Gamblang dan mampu dicerna secara kasat mata bahwa DPR mendorong keinginannya tanpa memedulikan kebutuhan bangsa. Keinginan untuk lolos dari tindakan pemberantasan rasuah di masa lalu, sekarang, dan masa depan melalui persuasinya kepada seluruh elemen masyarakat bertajuk Urgensi Revisi UU KPK. Kata “urgensi” untuk merevisi peraturan perundang-undangan hadir apabila dalam penerapan norma tersebut tidak menghasilkan efek yang signifikan terhadap cita awal norma ataukah sudah tidak bersahabat lagi dengan perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Dengan legitimasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan track record yang memuaskan.
Berdasarkan rapor akuntabilitas kinerja terhadap 86 K/L yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI pada tahun 2015, KPK berpredikat A dengan peringkat runner-up. Sedangkan penegak hukum lain seperti Kepolisian pada posisi 36, Mahkamah Agung pada posisi 51, dan Sang Jawara (dari belakang) adalah Kejaksaan Agung RI pada posisi 86. Audit akuntabilitas kinerja dari Kemenpan-RB, secara tidak langsung berbicara bahwa KPK bersama UU KPK merupakan “mitra” yang efektif.
Selain DPR memiliki motif yang ambigu, ternyata DPR tidak pula mempunyai komitmen dalam hal pemberantasan korupsi. Tertuang dalam poin menimbang huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Konsiderans di atas menggambarkan bahwa diperlukan extra ordinary method untuk menuntaskan extra ordinary crime. Hal ini inheren dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej bahwa diperlukan cara dan metode tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi.
Dekadensi Muatan RUU
Dalam konsiderans rancangan undang-undang (RUU) KPK bahwa pelaksanaan tugas KPK perlu ditingkatkan melalui pemberantasan tipikor yang lebih komprehensif. Namun, titik kontroversial RUU KPK yang tertuang dalam batang tubuh, antara lain penyadapan pada tahap penyidikan, pembentukan dan kewenangan Dewan Pengawas, kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan tertutupnya peluang merekrut penyidik dan penyelidik secara mandiri. Hampir pasti bahwa ada disparitas antara semangat konsideran RUU dengan batang tubuh.
Pertama, penyadapan dilakukan pada tahap penyidikan. Terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara disebabkan oleh kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan membuktikan bahwa hal tersebut mempercepat proses penindakan. Melihat kembali kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang disadap sebelum terjadi pemindahtanganan uang suap sehingga KPK dapat menekan proses kejahatan oleh “wakil Tuhan” pada tahap awal. Apabila penyadapan dilakukan pada tahapan penyidikan, operasi tangkap tangan (OTT) sudah tidak diperlukan karena bukti permulaan telah cukup dan penentuan tersangka pun telah paripurna.
Kedua, adalah pemberian kewenangan SP3 kepada penyidik KPK akan mendegradasi kualitas penyelidik dan penyidik KPK. Hal itu disebabkan tanpa kewenangan SP3 ketelitian dan teknik klarifikasi pada lembaga antikorupsi ini sangat ketat. Selain itu, tanpa SP3 KPK menjadi lembaga yang dituntut untuk selalu akuntabel dan profesional dalam menentukan tersangka koruptor. Selanjutnya, untuk menjaga penyidik KPK dari praktik mafia kasus yang memanfaatkan momentum ketika penyidikan.
Ketiga adalah rekruitmen penyelidik dan penyidik yang dikhususkan untuk Kepolisian dan Kejaksaan, dalam artian KPK tidak berwenang melakukan rekruitmen di luar aparat penegak hukum konvesional. Kerawanan yang terjadi ialah ketergantungan lembaga dan loyalitas ganda calon penyidik dan penyelidik KPK. Sedangkan kasus korupsi membutuhkan kompleksitas penanganan yang didasari oleh lintas cabang ilmu dan keahlian, bukan hanya kemahiran merumuskan unsur delik melainkan mampu melakukan pendeteksian awal di seluruh bidang yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi.
Keempat pembentukan dan kewenangan Dewan Pengawas. Berdasarkan pembentukannya, Dewan Pengawas berbentuk lembaga non-struktural pemerintah yang nanti akan menyebabkan tumpang tindih dan dualisme poros kepemimpinan dalam raga KPK. Berdasarkan kewenangannya, Dewan Pengawas dapat menghambat kinerja KPK dikarenakan seluruh izin penyadapan dan penyitaan dimiliki Dewan Pengawas. Sungguh ironi jika KPK ingin menyadap Dewan Pengawas itu sendiri, apakah izin tersebut akan diterima?
Ke Mana Rancangan UU Perampasan Aset dan Revisi UU Tipikor
Jika konsiderans RUU KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus lebih komprehensif sewajarnya amunisi pemberantasan segera dibahas dan dilegalkan. Hal ini sebagai konsekuensi zaman dan perubahan, termasuk inovasi di bidang kejahatan. Ibarat sebagai seorang prajurit, KPK bersenjatakan UU KPK beserta kekhususannya, namun senjata tersebut belum memiliki peluru-peluru yang dapat menembus “kevlar” tindak pidana korupsi dengan modernitas termutakhir.
Letak urgensi perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi terletak pada UU Tipikornya. UU Tipikor yang berlaku saat ini belum mengintroduksi norma-norma United Nations Convention Againts Corruption yang diratifikasi ke dalam UU No. 7 Tahun 2006. Illicit Enrichment, Bribery In the Private Sector, dan Trading in Influence adalah beberapa norma yang diharapkan mampu mendongkrak lingkup dan jangkauan pemberantasan korupsi. Ditambahkan pula berdasarkan penjelasan umum UU No. 7 Tahun 2006 bahwa dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan konsiderans undang-undang tersebut bahwa bahwa tindak pidana korupsi telah bertransformasi menjadi kejahatan transnasional.
Dari badan UU Tipikor sendiri, setelah terbit putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghilangkan kata dapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (3) sehingga tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dari delik formil (perbuatan) menjadi delik materil (akibat). Hal tersebut membuat Pasal 32 menjadi pasal mati dalam artian tidak berguna lagi. Selain itu, diferensiasi antara pemidanaan antara norma generalis (Pasal 2 ayat (1)) lebih berat dibandingkan norma spesialis (Pasal 3). Juga perbedaan mendasar antara suap dan gratifikasi, di mana titik perbedaan delik tersebut tidak nampak dan berpotensi menimbulkan tafsir ganda oleh penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Bahkan, berdasarkan definisi dalam UU Tipikor pun tidak ada yang menyebutkan gratifikasi adalah tindak pidana. Jika ditafsirkan secara autentik, maka yang tertuang pada Pasal 12B adalah tindak pidana suap. Maka, apabila keberpihakan politik hukum DPR terhadap pemberantasan korupsi tidak fiktif, segerakan revisi UU Tipikor.
Berdasarkan dorongan dari UNCAC 2003, adanya semangat untuk menguatkan pemberantasan korupsi lintas negara dalam kerja sama pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tipikor. Instrumen hukum nasional yang mengatur tentang perampasan aset yang nantinya menjadi pelegitimasi langkah-langkah aparat penegak hukum melakukan recovery aset yang diduga adalah hasil tindak pidana tanpa menunggu putusan pengadilan. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi tidak seoptimal yang diharapkan.
Deputi Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rimawan Pradiptyo mengatakan estimasi total biaya eksplisit akibat praktik korupsi sepanjang 2001-2012 mencapai Rp 168,19 triliun. Rimawan melanjutkan bahwa pelaku koruptor hanya didenda atau harus mengganti sebesar 8,97 persennya saja atau senilai Rp 6,27 triliun pada harga berlaku atau Rp 15,09 triliun pada harga konstan 2012. Hampir terkuras kering keuangan negara yang dikuras, pengembaliannya pun tidak mencapai 10 persen. Maka dari itu, RUU Perampasan Aset diharapkan mampu memotong rantai kebocoran pajak-pajak yang orang tua anda bayar (baca: keuangan negara).
Implikasi Kecacatan RUU
Kecacatan RUU KPK adalah bagian yang sangat fatal dari suatu penyusunan peraturan perundang-undangan, bahwa RUU KPK tidak memiliki naskah akademik. Terjadi ketidaksinkronan antara konsideran dengan penjelasan umum dan antara konsideran dengan batang tubuh. Implikasi tersebut bagian dari konstruksi peraturan perundang-undangan yang sejak awal dibentuk untuk melanggengkan otoritas koruptif.
Selain tanpa naskah akademik, berdasarkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2017 bahwa RUU KPK tidak masuk dalam daftar pada tahun ini. Badan Keahlian Dewanlah yang bersikeras untuk melakukan sosialisasi RUU KPK di beberapa universitas di Indonesia dan serentak penolakan pun terjadi. Seharusnya DPR tanggap terhadap aspirasi masyarakat, tetapi kali ini mereka bebal dan kebal terhadap suara rakyat. Entah apa yang menjadi motif kuat DPR, masih terbentuk entitas misteri dari ambiguitas revisi UU KPK.