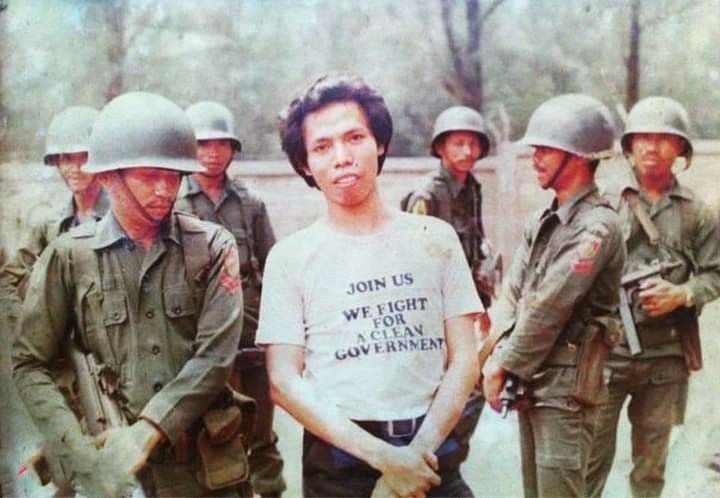Israwati Nursaid
Mahasiswi Teknik Informatika 2013
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia
Pernahkah Anda diasingkan oleh negara? Pernahkah Anda diasingkan oleh organisasi? Pernahkah Anda diasingkan oleh pasangan Anda? Jika tidak, maka hidup Anda tidaklah sempurna, perjuangan adalah perihal melawan arus, tersisih dari kecintaan akan manusia, institusi, ataupun alam sekitar merupakan totalitas perjuangan, begitulah penulis memahami makna kudeta. Ia hanya terjadi kerena putus cinta. Tidak semua orang bisa menikmati terasingkan. Maka beruntunglah manusia pilihan yang tak memiliki pasangan, tak berorganisasi dan tak bernegara. Ini tentu lebih baik karena memberi Anda kebebasan dalam bercinta tanpa mengenal batas ruang. Sejatinya, cinta merupakan kebutuhan dalam menghidupkan peradaban.
Sekadar merefleksi ingatan masyarakat bahwa 3 presiden Indonesia yang diturunkan paksa dari jabatannya dengan beragam cara dan kepentingan membuat trauma tersendiri bagi rakyat Indonesia, diibaratkan sebuah luka, para pemimpin negara telah tersayat dan sakitnya menjulur pada rakyat Indonesia. Di samping hal tersebut, masyarakat tetap percaya kebaikan daripada sebuah demokrasi yang mencipta kelas mayor juga minor, dipimpin oleh seorang pemimpin, diperbudak dibawah pimpinan. Tak ada ruang empati dari hal-hal yang dimaknai sebagai penindasan, puluhan juta massa menggantungkan hidup pada seorang pemerintah adalah penindasan, bersetubuh dengan pasangan sendiri tapi belum terikat pernikahan adalah perbuatan salah di mata negara, menjajakan diri demi sesuap nasi juga perbuatan salah di mata negara. Hingga hari ini peraturan terbaru khususnya di Jakarta, membuang air seni di sembarang tempat juga merupakan perbuatan salah di mata negara. Padahal, negara tak pernah sedikit pun berdiskusi dengan rakyatnya perihal kata salah. Lalu bagaimana kebenaran akan tercipta tanpa dialektika? Menjadi pemimpin yang adil bagi jutaan pemikir tidaklah gampang, pada dasarnya tiap individu memiliki indikator dalam menafsirkan teks, termasuk arti dari keadilan itu sendiri, bukankah lalai dalam memberikan hak warga negara adalah ketidakadilan? Namun, ketidakkebebasan pemerintah mengelola rakyatnya juga adalah ketidakadilan? Sangat tumpang tindih tapi begitulah sistem pemerintahan mencipta penindasan.
Memaknai Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai manusia adalah bentuk keadilan dan apresiasi terhadap resiko pemerintahan. Ketiga presiden ini mengalami kudeta, yakni diturunkan dari jabatannya secara nirkekerasan dan menggelikan dengan tontonana drama negeri saat peran antagonis dimainkan. Dalam memaknai teks Coen Husain Pontoh dalam buku Ketika Demokrasi Melahirkan Kudeta mengatakan bahwa, kudeta bukanlah satu-satunya jalan menuju negara yang lebih demokratis karena di setiap kudeta selalu ditunggangi oleh kepentingan. Siapapun akan mengatakan dirinya demokratis, mengkritik pemimpinnya otoriter dan lain sebagainya, lagi-lagi bersikap demikian itu bukanlah solusi, menggantungkan kemerdekaan pada kerja keras satu orang merupakan masalah besar bagi diri sendiri, karena jika ia tak terlaksana maka kecewa menjadi air yang harus diteguk. Jadi, memimpikan seorang pemimpin yang ideal yang bisa melayani puluhan juta kemauan rakyat hanyalah fatamorgana, kecuali seluruh dokter membedah otak manusia menjadikan semua saraf manusia sama atau para agamawan berkumpul menyajikan kultum pada seluruh umat manusia secara massif hingga pemikiran antara manusia satu dengan manusia lainnya menjadi searah, ini merupakan kekonyolan semesta. Mencapai puncak kemerdekaan bukanlah hal semudah memerintah karena hal pertama adalah terbebas dari perintah itu sendiri. Manusia sebagai individu harus bergerak untuk kemerdekaaan dirinya terlebih dahulu. Kita telah belajar dari situasi di mana kekacauan adalah ketidaktoleran atas pikiran dari masing-masing manusia di muka Bumi.
Indonesia telah terlanjur bernegara, dipimpin oleh seorang presiden, seperti juga kebanyakan organisasi lainnya yang memiliki pemimpin. Organisasi adalah wadah yang menampung sekumpulan manusia yang memiliki visi yang sama, namun karena terlalu banyaknya tujuan dari beranak-pinaknya organisasi di Indonesia, tanpa sadar telah menghadirkan arogansi identitas, lupa bahwa tujuan utama berorganisasi adalah mencipta perdamaian. Kini, tujuan telah melukai persatuan, negara telah melukai idealismenya, Pancasila. Organisasi sebagai sub negara adalah simulasi, di dalamnya dilanggengkan penindasan. Sistem yang merujuk pada tanggung jawab besar yang dilimpahkan kepada pemimpin suatu organisasi menjadi fenomena bahwa apa yang terjadi manusia lainnya adalah tanggung jawab manusia satu, ketidakbecusan manusia lainnya berarti ketidakbecusan manusia satu. Bukankah semua orang harusnya merdeka dari sifat dan sikap pasif? Karena itulah otoritas tertinggi dari seorang individu. Akibat hentakan sistem tak jarang jika manusia satu dan manusia lainnya saling menikam karena sistem yang terbangun. Adat bernegara telah memperlihatkan bagaimana kehidupan ini membutuhkan manusia heroik bagi manusia lainnya yang mampu menjamin nasib rakyat pada telunjuk kekuasaan.
Memaknai Kudeta
Kudeta terselip dalam drama pacaran. Hanya saja tak semua manusia mampu mengibaratkannya. Di antara berpuluh perempuan, laki-laki akan memilih seseorang untuk dijadikan pasangan, ataupun sebaliknya. Kudeta ibarat putus cinta dari pasangan, apakah mereka sepakat bahwa orang yang paling disenangi ialah sang pemimpin, pemimpin yang lahir dari pilihan sendiri, bukan? Dengan segala pengorbanan yang ia lakukan untuk mencari kebaikan organisasi atau negara, tak bisa dijadikan satu-satunya acuan kemajuan masyarakat. Setiap individu perlu berpikir bahwa nasib dirinya berada di tangannya sendiri, pada kakinya sendiri serta pada kepalanya sendiri. Pembangunan PLTA di Seko, penambangan pasir laut di Takalar, penggusuran di Bara-baraya, dan pembangunan bandara internasional Kulon Progo, Jokjakarta, New Yogyakarta International Airport (NYIA) adalah sederet luka petani, nelayan, dan kaum miskin kota yang tersayat pembangunan sang kuasa dan pengusaha. Mahasiswa dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut bersolidaritas dengan mengangkat diri sebagai kaum intelektual sebagai wujud tanggung jawab atas berpuluh-puluh buku yang telah ditamatkan, yakni membela hak rakyat atas ego sang pemegang keputusan, yakni pemerintah.
Pemerintah yang dirujuk adalah seorang pemimpin yang memegang kendali pemerintahan, dan rakyat mecitrakan diri sekadar kelompok. Melirik tulisan Emma Goldman mengenai Mayoritas vs Minoritas, pemerintah sudah selayaknya mengikuti suara rakyat. Penolakan penggusuran dan pengerukan mengatasnamakan usaha apapun harusnya segera dihentikan namun inilah celahnya berdemokrasi, hanya sebuah kesia-siaan. Hak mayor harusnya terpenuhi jika si minor mengkehendaki. Bernegara telah mencerminkan bagaimana hak diri dipegang oleh si pemimpin, dan rakyat telah kehilangan dirinya sendiri sesuai dengan Soren Kierkegaard dalam buku Makna Cinta bahwa ketika orang gagal atau tidak memilih untuk dirinya sendiri dan membiarkan orang lain memilih bagi dirinya sendiri maka saat itulah individu kehilangan dirinya.
Perjuangan dan kesungguhan Soekarno dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, kemelut suasana hati serta pikiran pra kemerdekaan mengantar Soekarno dan kawan-kawannya mencipta sejarah revolusi Indonesia. Tak heran jika beragam julukan diberikan padanya, dari bapak revolusi, singa podium, dan panglima perang. Sebagai salah satu sosok penginspirasi, ia hebat dengan pemikirannya dalam menggerakkan rakyat. Pada tahun 1965 di New York diterbitkan buku Soekarno An Authobiography As Told To Cindy Adams yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsu Hadi dan dicetak oleh Yayasan Bung Karno dengan mengalami sebanyak empat kali revisi sejak tahun 2007, 2011, hingga tahun 2014 sebanyak dua kali revisi. Dalam buku tersebut yang telah diterjemahkan berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Cindy Adams, banyak bercerita tentang sosok Soekarno dimasa kecil mulai dari kelahirannya 6 Juni 1901 hingga pasca kemerdekaaan seperti diakuinya Indonesia oleh Negara lain, tak terlepas dari bentuk penjajahan lainnya.
Putus Cinta
Putus cinta adalah awal penindasan. Tak memiliki pasangan ataupun kawan untuk berjuang begitu menyedihkan sama dengan putus cinta. Putus cinta adalah awal dari segala kekacauan. Memilih bernegara lalu memusatkan kesejahteraan sosial oleh satu tangan, maka rakyat sama bodohnya dengan mereka yang diatur oleh aturan bernegara. Tak lahir di zaman pembuatan aturan lalu mengikuti segala aturan yang telah ada, maka hari ini, penulis deklarasikan bahwa generasi sekarang adalah generasi budak. Manusia-manusia yang mengatakan dirinya bukanlah sapi yang dituntun tapi lebih mengerikan dari binatang tersebut, seperti itulah manusia yang dituntun. Mereka lupa bahwa manusia terlahir membawa kebebasan dan pantas menikmati cinta. Dalam Works of Love-Kierkegaard menggambarkan bentuk tertinggi dari cinta sebagai pengabaian diri total sehingga orang meniadakan perhatian terhadap dirinya sendiri. Pengabaian terhadap diri sendiri adalah bentuk putus cinta terhadap diri sendiri. Karena makna dari cinta sendiri adalah merawat tanpa pamrih.
Meski dalam menafsirkan cinta, kita akan berpegang pada definisi masing-masing, tetapi perspektif lainnya adalah pelengkap dari suatu perspektif. Namun, membenarkan sebuah perspektif lalu menyalahkan perspektif lainnya maka itu juga adalah bentuk putus cinta. Sejak terbentuknya aturan-aturan berlandaskan negara maka saat itu pula tercipta teori benar dan salah juga sanksi dan hadiah. Bukankah itu tidak lagi memanusiakan manusia? Kita perlu membebaskan diri dari aturan-aturan yang menindas kemanusiaan, saat mengamati pataka-pataka aksi yang sering dilakukan di bawah jalan layang Pettarani dan Urip Sumoharjo, Makassar, hal yang menggelitik ketika aksi hari anti kekerasan terhadap perempuan, pataka yang dipegang oleh seorang perempuan bertuliskan, “Jangan salahkan pakaian kami, salahkan negara melanggengkan kekerasan,” ini merupakan sangat kontradiksi dengan perkataan Emma Goldman, bahwa untuk menuju revolusi tak cukup dengan mendatangi pemilu lalu menjatuhkan pilihan pada calon pemimpin. Kekerasan terhadap perempuan harus diminimalisir oleh perempuan itu sendiri bukan dengan menuntut hak tanpa ada upaya untuk memperkuat diri perempuan itu sendiri. Mengemis hak pada konstitusi yang telah disajikan oleh negara sama dengan meminta uang pada si miskin atau bersedekah pada si kaya, semua hanyalah kesia-siaan. Satu-satunya jalan adalah menebar kesadaran pada masyarakat karena masih banyak diantara kita yang sadar namun pesimis kesadaran tersebut boleh ditularkan, tapi seperti itulah belajar. Untuk mencapai hal yang totalitas semua butuh usaha yang keras. Lalu apakah penyebaran kesadaran itu mampu terealisasi ?
Buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis oleh Cindy Adams menguak cerita betapa susahnya Soekarno mencapai puncak kemerdekaan, ia harus keluar masuk penjara, mengabaikan hak-hak istrinya, bergonta-ganti pasangan revolusi hingga akhirnya ia mampu membangun massa untuk melawan kolonialisme. Lalu mengapa di era serba instan dan santai ini kita tak bisa serius dalam membangun penyadaran masyarakat? Tentunya tak akan sesusah masa Soekarno dalam buku tebalnya, pikiran keras memaksanya tetap berpikir metode untuk memerdekakan Indonesia, memanfaatkan masa pendudukan Jepang membuatnya terlihat menjilat oleh rakyatnya. Namun, tidakkah masyarakat menikmati kemerdekaan itu hingga hari ini? Meskipun tak sepenuhnya, tapi perjuangan bung Karno memerdekakan Indonesia patut diapresiasi meski berujung penurunannya sebagai presiden Indonesia dengan Surat Perintah Sebelas Maret yang dikenal dengan Super Semar dimana surat tersebut masih bersifat tanda tanya karena tak pernah tampak naskah aslinya, namun dalam surat tersebut Soeharto mengganggap dia adalah pengganti Soekarno.
Dalam sub judul bab terakhir Putus Cinta dan Penyebab Sembuhnya, Emma Goldman dalam buku Ini Bukan Revolusiku menyampaikan bahwa putus cinta terjadi sejak adanya teori kepemilikan, maka menafsir teks tersebut sudah selayaknya kepemilikan harus dihancurkan, bukan sekadar alat produksi namun cinta itu sendiri bukanlah monopoli individu.
Mencipta Kolektivisme
Cinta (love) adalah kata yang memiliki arti penting di dalam hidup manusia. Akan tetapi kata ini dapat dengan mudah berubah menjadi benci (hate) ketika individu disakiti atau dikhianati. Adanya ketergantungan pada situasi dan kondisi tertentu menjadikan sang diri bertindak dalam kecenderungan atau preferensi. Akibat dari preferensi diri, orang terhalang untuk mencintai semua orang (neighbour) secara tulus. Sikap mencintai berdasarkan preferensi menjadikan diri individu tidak sungguh-sungguh mempraktikkan arti sesungguhnya dari mencintai seperti Erich Fromm dalam buku Seni Mencintai bahwa Cinta bukan semata-mata suatu hubungan dengan seseorang; anta adalah sikap, suatu orientasi karakter yang menentukan keterkaitan seseorang dengan dunia keseluruhan, bukan pada satu objek. Meski kebanyakan orang meyakini bahwa cinta ditimbulkan oleh objek, bukan oleh kemampuan. Bahkan mereka percaya, bila mereka tidak mencintai orang lain selain orang yang mereka “cintai” itu, adalah bukti dalamnya cinta mereka. Ini merupakan kekeliruan yang sama dengan yang telah kita bahas diatas. Karena dia tidak mengerti bahwa cinta adalah tindakan, kekuatan jiwa, dia meyakini bahwa yang perlu dia temukan adalah obyek yang tepat – dan bahwa segalanya akan berjalan dengan sendirinya sesudah itu.
Dalam Seni Mencintai, Sikap itu seperti orang yang ingin melukis, tapi bukannya mempelajari seni, dia malah menunggu obyek yang tepat, dan yakin akan melukis dengan indah saat dia sudah menemukan obyeknya itu. Jika aku sungguh mencintai seseorang, maka aku mencintai semua orang, aku mencintai dunia, aku mencintai kehidupan. Jika aku bisa berkata pada orang lain, “Aku mencintaimu,” aku juga harus bisa berkata, “Dalam dirimu aku mencintai semua manusia, melaluimu aku mencintai dunia, dalam dirimu juga aku cintai diriku.”
Bagi Kierkegaard, melankoli adalah jenis penyakit yang diidap orang-orang pada zaman-nya dan hal ini menjerumuskan manusia ke dalam keputusasaan. Menurut Kierkegaard, “Zaman kita cukup melankoli untuk menyadari bahwa ada hal yang disebut ‘tanggung jawab’, dan bahwa hal ini menunjuk pada sesuatu yang penting. Semua orang ingin berkuasa, namun tak seorang pun mau menerima tanggung jawab.”
Bagi Post, cinta yang saling memberi patut dinilai positif karena cinta itu melahirkan kesukaan dan kesenangan bagi kedua belah pihak. Jika kita sepakat bahwa cinta adalah representasi dari sikap dan sifat menyayangi, memuji, mengagumi, merindukan dan lain sebagainya maka kita adalah teman, namun meski kamu tak sepakat maka kita tetaplah berteman karena itu adalah kebebasan tiap individu untuk berpikir. Berbicara masalah cinta kita kadang mengenyampingkan bahwa dengan orang tua pun kita sedang menjalin cinta. Kebanyakan wacana akan merujuk pada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan menjalin hubungan yang dimaksud dengan pacaran. Pada umumnya, laki-laki akan menyatakan perasaannya kepada si perempuan dan si perempuan akan menanggapi. Apakah tanggapannya bersedia atau tidak yah tergantung bagaimana si perempuan bersikap. Jika ia menerimanya, berarti ia telah siap menyesuaikan dengan kepala lainnya. Jika tak mampu menyesuaikan lagi maka tidak ada jalan lain selain putus cinta. Untuk mengobati putus cinta tak cukup dengan mencari pasangan baru, mencintainya lalu melupakan pengorbanan yang telah lalu. Seperti tulisan Bima dalam tulisan Kuasa dan Birahi pada sebuah website maka semua yang ada di dunia ini bersifat politis termasuk cinta. Cinta adalah alat untuk saling menguasai. Dengan mengandalkan cinta, semua bisa dimenangkan pun dijatuhkan, tak terkecuali pasangan.
Dalam situasi pacaran, apapun cenderung dilakukan lainnya untuk saling membantu, atas nama kolektif,. penindasan pun dimassifkan. Ancaman putus kadang liar terbisik di telinga. Sebagian orang menganggap putus cinta adalah takdir, bukan jodoh, pasrah pada keadaan dan akhirnya dikuasai oleh pasangan. Dengan mengatasnamkan negara ataupun agama, keduanya hanyalah alat yang dibumbui kata cinta. Ketika cinta negara, engkau akan jadi patriotisme, resikonya mati atas nama negara. Dalam agama diteguhkan dengan kata jihad, mati di jalan Tuhan yang Maha Esa. lalu apakah manusia tak berpikir bahwa tuhan juga bisa putus cinta ? seperti keyakinan bahwa tuhan akan memasukkan manusia ke dalam neraka, lalu membakar manusia atas segala kejahatan yang telah mereka perbuat. Terlepas dari semua tindakaan memiliki alas an masing-masing namun jangan sampai cinta dan kebencian jua dijadikan alat menguasai satu sama lain. Jika rasa saja mampu memonopoli satu sama lain maka apalagi yang murni dari sifat manusia ? jika kawan mampu berkhianat maka siapa lagi yang akan dipercaya ? seperti halnya pemerintah dan rakyat. Jika mereka tak mampu menjalin cinta maka yang hadir hanyalah penindasan yang terangsang akibat putus cinta, lupa mereka bahwa cinta adalah obat ampuh dalam menetralisir kelas dan perbedaan.
Jika teks romantis dari Plato dalam buku Simposium (Hakikat Eros, Cinta, dan Manusia) yang diterjemahkan oleh Eka Oktaviani mengatakan, “Sayangku Socrates, kehidupan manusia semestinya dijalani: di dalam perenungan terhadap keindahan. Jika suatu saat kau mendapatinya, cinta tidak akan tampak bagimu sebagai emas, pakaian, anak laki-laki atau pemuda yang tampan sebagaimana saat ini kau terkesima olehnya; kau dan banyak orang lain siap untuk menghadapi kehidupan dengan yang kau cintai kemudian hidup bersama selamanya, seandainya itu memang memungkinkan, tidak untuk minum ataupun makan bersama, tetapi hanya untuk selalu memandang dan bersama, tetapi hanya untuk memandang dan bersama satu sama lain, yang separuh merindukan separuh yang lain, dan mereka merangkulkan lengan mereka satu sama lain dan saling menjalin, berharap untuk tumbuh bersama menjadi utuh, mereka sekarat oleh kelaparan dan kelumpuhan karena mereka enggan untuk melakukan sesuatu jika terpisah satu sama lain, maka Erich Fromm membebaskan kepemilikan cinta tak bertumpu pada kekasih melalui teks, “Jika Seseorang mencintai hanya satu orang dan tak acuh dengan orang-orang lain, cintanya bukanlah cinta melainkan keterikatan simbolik, atau egoisme yang meluas.” Sepakat dengan hal tersebut maka cinta adalah senjata kolektivisme dalam membangun peradaban yang penuh kebaikan, tugas manusia adalah bercinta setiap waktu terhadap sesama makhluk hidup juga lainnya tak terkecuali pemerintah kepada rakyat karena tak dapat dipungkiri bahwa dengan bercintalah yang melahirkan peradaban baru.