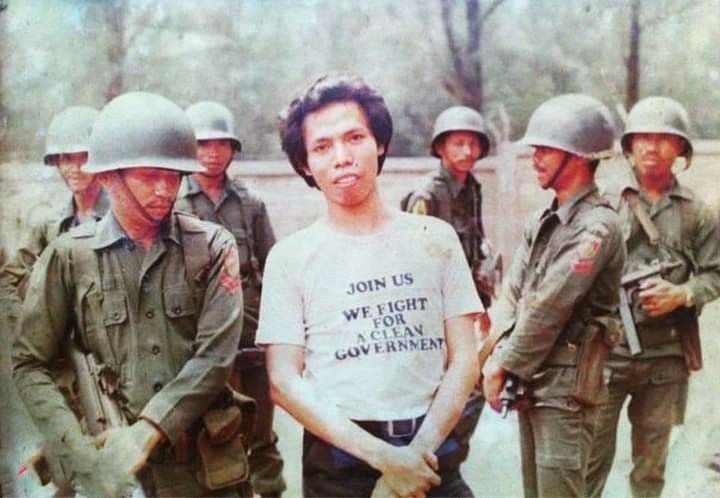Oleh: Muhammad Ikhsan
(Kordinator Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan HMI Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin periode 2017-2018)
Isu lingkungan saat ini menjadi isu yang sangat penting dikarenakan, hal tersebut berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Perdebatan mengenai eksploitasi terhadap alam sudah sejak lama menjadi bahan pertikaian baik dalam tingkat global maupun nasional. Sejak dahulu semangat penguasaan terhadap sumber daya alam kemudian menjadi spirit bagi pembenaran terhadap tindakan kolonialisme yang dilakukan oleh negara- negara besar dalam sejarah peradaban manusia.
Indonesia adalah salah satu negara di dunia pernah mengalami proses penjajahan dalam waktu yang sangat lama dari negara-negara seperti Portugis, Inggris, dan Belanda dimana alam menjadi motif penjajahan. Tidaklah mengherankan jika kemudian aturan, nilai-nilai serta hukum yang mengatur tentang sumberdaya alam sangat dipengaruhi dengan kebijakan dari negara penjajah.
Menurut Blaikie and Brookfield tahap pertama yang dilakukan dalam rangka penguasaan sumber daya alam di Benua Asia dan Afrika, adalah dengan melakukan klaim bahwa semua lahan adalah milik negara.
Dalam konteks Indonesia, pengaruh klaim pemerintahan Belanda di negeri Hindia Belanda masih sangat terasa sampai sekarang. Terutama yang kemudian terinternalisasi dalam konstitusi dasar Indonesia tentang domain negara atas sumber daya alam. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945. Atas dasar pasal ini juga kemudian, sumber daya alam dieksplotasi sebesar-besarnya demi kepentingan manusia.
Penggerusan terhadap sumber daya alam kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana alam. Bencana alam sejatinya dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Turunnya kualitas lingkungan tersebut, mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainya. Sehingga memang perlu progresivitas dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan.
Tinjauan filosofis akan isu lingkungan yang sangat jarang di Indonesia. Stagnasi teori lingkungan sampai pada etika lingkungan, menyebabkan kemiskinan kajian dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Walau sebenarnya gerakan komunitas lingkungan di Indonesia sudah banyak.
Namun, mengapa sampai hari ini kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan itu sangat minim?
Hal tersebut menjadi problematika bagi penggiat gerakan yang pro terhadap lingkungan saat ini. Bagi Indonesia sendiri, sumber daya dan keanekaragaman hayati sangat penting bahkan, menjadi sesuatu hal yang strategis untuk keberlangsungan kehidupanya bangsa.
Hal ini bukan semata-mata karena posisi Indonesia sebagai salah satu negara terkaya di dunia atas keanekaragaman hayatinya semata. Namun, dewasa ini lingkungan tidak begitu dihargai. Pengerusakan lingkungan itu dianggap hal yang wajar saja dan dilakukan dengan penuh kesadaran tinggi. Hukum pun tidak dapat lagi berbuat banyak.
Dampaknya begitu terasa. Kita bisa melihat dampak dari kerusakan tersebut melalui media maupun dengan mata kepala sendiri. Sampah berserakan dimana-mana, pengundulan dan penggurunan hutan (deforestasi) kerap terjadi, asap pabrik kita hirup sehari-hari, serta diikuti dengan eksploitasi alam secara berlebihan dan brutal.
Tidak heran jika, musim penghujan tiba banjir terjadi, dan tanah longsor mengikuti. Begitu juga sebaliknya di saat kemarau, kita dihadapkan dengan kekeringan panjang, kebakaran hutan, polusi udara, tanah dan air. Oleh karena itu, perlu sebuah gagasan baru dalam menjawab kebuntuan etika lingkungan dalam memahami lingkungan itu sendiri.
Relasi Manusia dan Lingkungan
Beberapa pemikir sosial politik yang secara relatif membahas persoalan tindakan manusia dan eksploitasi alam, seperti Sigmund Frued misalnya, seorang psikoanalisis yang telah melakukan tinjauan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan.
Freud berpendapat bahwa atas nama kemanusiaan telah muncul sikap solidaritas massif untuk kemudian mengatakan bahwa, alam merupakan musuh bersama manusia yang harus ditunddukkan. Dengan pendapat demikian, cukup alasan untuk menunddukan alam.
Senada dengan Frued, Marcuse seorang tokoh mazhab Frankfurt dalam karyanya One Dimensional Man secara eksplisit menegaskan bahwa, dominasi terhadap alam terkait dengan dominasi sesama manusia, hal ini terjadi karena manusia dan alam dilihat sebagai komoditas dan nilai tukar. Sehingga dehumanisasi tidak dapat terhindarkan, begitu pula dengan eksploitasi terhadap alam.
Kritik Terhadap Etika Lingkungan
Marcuse juga menjelaskan mengenai filsafat Barat maupun dalam Islam, terkait teori lingkungan hidup yang telah menjadi doktin pokok ajaran dan falsafah kehidupan.
Dalam khazanah Filsafat Barat misalnya, ada tiga teori etika lingkungan yang muncul, yaitu:
1) Shallow Enviromental Ethics atau dikenal dengan antrophosentrisme;
2) Intermediate Enviromental Ethics atau biosentrisme; dan
3) Deep Enviromental Ethics atau ekosentrisme.
Antrophosentrisme adalah etika yang meletakkan nilai tertinggi pada manusia dan kepentingannya. Manusia dan kepentingannya dianggap menjadi hal yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan kebijakan yang akan diambil terkait dengan alam.
Konsekuensi dari antrophosentrisme adalah bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia; etika hanya untuk manusia. Hampir tak terbantahkan, nalar antroposentrisme merupakan penyebab utama munculnya krisis lingkungan.
Antrophosentrisme juga merupakan salah satu etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat ekosistem. Bagi etika ini, nilai tertinggi dan paling menentukan dalam tatanan ekosistem adalah manusia dan kepentingannya.
Dengan demikian, segala sesuatu selain manusia (the other) hanya akan memiliki nilai jika menunjang kepentingan manusia, ia tidak memiliki nilai di dalam dirinya sendiri. Oleh karenanya, alam pun dilihat hanya sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia semata. Cara pandang antroposentris ini, menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras sumber daya alam dengan semaksimal mungkin demi kelangsungan hidupnya.
Franz Magnis-Suseno menilai bahwa cara manusia modern menghadapi alam bersifat teknokratik, yakni menempatkan alam sebagai objek yang harus dikuasai dan diambil manfaatnya. Tak pelak, krisis lingkungan pun sulit terhindarkan, karena alam tidak mampu lagi berdaya menahan gempuran keserakahan manusia.
Diantara pengamat yang sepakat bahwa antroposentrisme menjadi biang keladi dari krisis lingkungan adalah Fritjof Capra. Menurut Capra, dengan pandangan antroposentrisme ini, segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki nilai dan harus diperhatikan, dengan catatan jika segala sesuatu itu menunjang dan dapat memenuhi kepentingan manusia.
Selain itu menurut Capra juga, jika pandangan ini terus digunakan, maka pengabaian terhadap lingkungan akan terus terjadi. Paradigma mekanistis Cartesian-Newtonian-Baconian telah menyebabkan masyarakat arogan dan menjadikan lingkungan sebagai objek yang harus dikuasai.
Sementara biosentrisme memperluas pemberlakuan etika bagi seluruh komunitas biotis, bukan hanya bagi manusia. Menurut teori ini, setiap kehidupan di bumi dipandang bernilai pada dirinya. Sehingga mempunyai nilai moral yang sama, terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia.
Sedangkan ekosentrisme memperluas etika dari komunitas biosentrisme kepada komunitas ekologi seluruhnya. Salah satu versi ekosentrisme adalah Deep Ecology (DE) yang diperkenalkan oleh Arne Naess, filsuf asal Norwegia (1973).
Beberapa pemikir juga menjadikan ekosentrisme sebagai fondasi dasar pemikiranya, serta meletakan alam sebagai pusat dalam memahami lingkungan. Aldo leopold seorang tokoh ekologi yang mengembangkan teori Etika Tanah (Land Ethic) salah satunya. Leopold berkontribusi mengkritisi kebudayaan manusia yang terlampau mendahulukan kepentingan dan kebutuhanya tanpa mempertimbangkan alam. Leopold mengalihkan konsentrasi pembahasan etika lingkungan yang cenderung simbiosi antara manusia dan alam, menjadi lebih memprioritaskan alam.
Hal tersebut yang dikritik Saras Dewi, ia beranggapan bahwa gagasan Leopold tersebut mengabaikan pembahasan mendalam perihal manusia sebagai subjek yang independen, bagaimana manusia membangun relasi dengan alam.
Perang Islam Terhadap Kejahatan Ekologis
Berangkat dari adanya etika lingkungan yang dipandang masih sekuleristik inilah, akhirnya menjadi memantik intelektual pemikir Muslim untuk mengemasnya menjadi etika lingkungan yang berwawasan keagamaan (baca: teologis).
Salah satu pemikir muslim yang memberikan perhatian serius dalam masalah etika lingkungan yakni, Sayyed Hosein Nashr. Dengan teori Scientia Sacra-nya, Nashr mengajak agar manusia kembali ke akar spiritualnya: dia harus kembali kepada kesucian dirinya, Tuhan dan Alam. Lingkungan merupakan lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh muslim.
Problem ini tidak lepas dari pemahaman umat Islam selama ini yang menganggap bahwa, kewajiban berlaku islâmî (dalam pengertian tunduk untuk pengabdian kepada Allah) hanya berorientasi kepada keselamatan akidah (mu’âmalah ma’a Allâh) dan ijtimâ’iyyah (mu’âmalah ma’a an-nâs) saja.
Padahal Allah SWT telah meng-amânah-kan pada manusia tiga hal yang perlu dijaga agar tidak termasuk orang yang fasik.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah [2]: 2627 yang berbunyi:
- Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?,” dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,
(yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka Itulah orang-orang yang rugi.
Konsep teologi lingkungan tersebut, mengandung makna penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam. Makna tersebut yakni, penghormatan yang saling keterkaitan bagi setiap komponen dalam aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk. Lebih lanjut, bermakna juga untuk menunjukkan bahwa etika (akhlak) harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama tidak saja peduli, akan tetapi mempunyai komitmen yang jelas dan tegas tentang lingkungan. Komitmen lingkungan ini tidak hanya dituangkan dalam bentuk asas untuk etika lingkungan yang bersifat normatif akan tetapi, juga dalam aras praktis. Islam juga telah melahirkan seperangkat hukum atau peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan alam.
Daftar Bacaan:
San Afri Awang, Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. 27
Ibid.hlm 37.
Lihat Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan (Yogyakarta:PT LKIS, 2009), hlm. 11.
Lihat Franz Magnis Suseno, Etika Sosial (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 197.
Lihat, Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, terj. M. Toyyibi (Yogyakarta: Bentang, 1997), hlm. 150-152.
Saras Dewi, Ekofenomenologi Mengurai Disekuilebrium Relasi Manusia dengan Alam. (Tangerang : Marjin Kiri) hlm. 36.
Syarifuddin,Pencemaran lingkungan dalam prespektif fiqh, 2013.
Ahmad Hatta, Tafsir Al-Qur’an, 2009