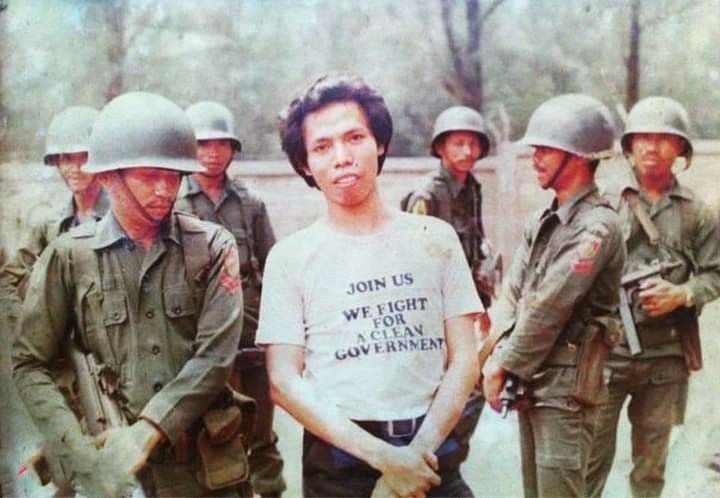Oleh: Ahkamul Ihkam Mada
Akhir-akhir ini, publik diramaikan dengan perdebatan terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendibudristek) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ada yang menganggap peraturan menteri tersebut adalah angin segar bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang sampai saat ini masih sering terjadi, ada pula yang menganggap peraturan menteri tersebut menjadi tindakan pemerintah yang secara tidak langsung melegalkan zina dan seks bebas di lingkungan kampus. Mulai dari media mainstream, sampai pada kolom komentar media sosial, masih sangat panas dipenuhi dengan berbagai macam argumen mereka yang pro maupun kontra, dan bahkan paling buruk, kata-kata bernada pelecehan terhadap mereka yang berani bersuara juga masih ditemukan.
Dikutip dari portal berita Tempo, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemdibudristek pada tahun 2020, dari keseluruhan responden 77% yang merupakan dosen menyampaikan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus, dan 63% diantarnya tidak melaporkan kekerasan seksual tersebut. Tanpa sadar, disaat ruang publik dipenuhi dengan perdebatan-perdebatan diluar sana ada mereka yang menyimpan peristiwa yang mungkin saja sudah lama mereka alami tanpa ada tindakan untuk melaporkan. Survei tersebut dilakukan pada tahun 2020, pada saat itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memang telah menjadi isu serius yang terus diangkat sejak dulu ke ruang publik dan pemerintah melalui RUU PKS. Namun, seakan tak digubris, RUU PKS sampai saat ini juga belum disahkan menjadi Undang-undang.
Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, saat ini terjadi kekosongan hukum terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus. Namun, perlu diketahui bahwa dalam Pasal 289 KUHP sebenarnya tindak pidana yang mengarah pada kekerasan seksual yaitu perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan yang telah diatur, artinya kekosongan hukum terhadap penanganan kekerasan seksual tidak sepenuhnya terjadi. Namun, pasal 289 KUHP hanya melakukan tindakan penanganan dalam lingkup pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Sedangkan hal-hal yang hadir sebagai sebab dan akibat dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku tidak bisa diselesaikan dengan cara hanya memberikan sanksi pidana. Kompleksitas permasalahan yang timbul dan mendasari terjadinya tindak kekerasan seksual sangat rumit dan memerlukan penanganan yang mencakup keseluruhan sebab dan akibat dari perbuatan pelaku.
Berdasarkan hal tersebut, lahirlah kemudian Permendikbudristek yang saat ini menjadi pro kontra di masyarakat. Jika dilihat lebih jauh, peraturan menteri ini hadir tidak hanya untuk menghakimi pelaku sebagai akibat dari perbuatannya. Namun, juga untuk mengakomodir keseluruhan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak kekerasan seksual. Dibuktikan dari adanya upaya pencegahan, penanganan korban, sanksi administratif terhadap pelaku, sampai kepada satuan tugas yang dibentuk dalam rangka mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual serta trauma yang dirasakan oleh penyintas kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi. Sangat mulia tujuannya, secara substantif juga peraturan menteri ini sudah sangat jelas memberikan langkah apa yang harus ditempuh perguruan tinggi untuk mengatasi masalah lama yang terus terjadi di lingkungan kampus ini. Namun, layaknya kebijakan pemerintah pada umumnya, kepentingan dan pandangan setiap pihak tidak akan terpenuhi secara keseluruhan. Akan ada pihak-pihak yang setuju maupun tidak setuju. Dalam kasus peraturan menteri ini sendiri, kelompok organisasi dan lembaga Islam besar seperti Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa kelompok maupun individu lain menyatakan sikap menolak Permendikbudristek ini. Secara umum sikap penolakan yang diambil, didasari atas satu frasa dalam Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 ini, yaitu frasa “tanpa persetujuan korban”. Para pihak yang kontra berpendapat bahwa frasa tersebut menimbulkan penafsiran yang ambigu terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini. Mereka berpendapat bahwa jika yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban, maka perbuatan yang diterangkan dalam peraturan menteri tersebut jika dilakukan dengan persetujuan korban maka boleh saja, hal ini menurut mereka sama dengan bentuk pelegalan seks bebas dan zina.
Secara umum para pihak yang kontra juga tidak memiliki masalah pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Khudzaifah Dimyati, wakil ketua Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah selaku salah satu pihak yang kontra juga mendukung penuh terhadap hadirnya peraturan menteri ini. Namun, satu frasa yang menurutnya memiliki ambiguitas tersebut dapat menjadi masalah baru dalam penerapan peraturan menteri ini dan perlu untuk dicabut dan/atau direvisi.
Seks bebas dan zina memiliki domain yang berbeda
Pasal 5 ayat 2 huruf i telah mendudukkan bahwa, kekerasan seksual, salah satunya meliputi, “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban”. Begitulah salah satu bunyi dari Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini. Bagian tersebut menjelaskan salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang didefinisikan dalam peraturan menteri ini. Pada bagian akhir terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang menjadi pokok permasalahan yang saat ini masih diperdebatkan publik. Sedikit masuk kepada pembahasan, perlu kita ketahui bahwa peraturan menteri ini memiliki fokus pembahasan pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya hal-hal yang berada diluar ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak menjadi domain dari peraturan menteri ini. Terkait dengan kontroversi frasa “tanpa persetujuan korban” yang saat ini dipermasalahkan, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa frasa tersebut dikhawatirkan akan memiliki penafsiran ganda dan bisa menjadi pintu masuk pelegalan zina dan seks bebas di lingkungan kampus. Berdasarkan duduk permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa, kekhawatiran dari pihak kontra, mengarah kepada domain tentang peraturan seks bebas dan perzinaan yang tentu saja berada pada ranah yang berbeda dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual adalah sesuatu yang dilakukan dengan paksaan dan sangat jelas bahwa paksaan dilakukan tanpa persetujuan korban, sedangkan seks bebas dan zina, dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebuah kesalahan jika satu frasa yang berada pada sebuah aturan yang memiliki kekhususan terhadap ruang lingkupnya, kemudian diinterpretasikan terhadap sesuatu yang memiliki ruang lingkup atau domain yang berbeda.
Urgensi frasa “tanpa persetujuan korban“
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang membedakan antara kekerasan seksual dengan seks bebas dan zina adalah persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika frasa yang ada pada Permendikbudristek yang dipermasalahkan ini dihilangkan, ataupun diganti, maka akan mengubah makna dari kekerasan seksual itu sendiri. Frasa “tanpa persetujuan korban”, merupakan frasa utama yang menjadi unsur dalam pasal tersebut dan kemudian memberikan batasan dalam pendefinisian perilaku seksual dengan kekerasan. Tanpa adanya batasan yang diberikan oleh frasa tersebut, suatu perbuatan seksual dengan kekerasan, tidak bisa didefinisikan sebagai tindak kekerasan seksual.
Hal seperti ini bukanlah hal baru dalam tatanan aturan perundang-undangan. Dalam domain yang sama, KUHP telah mendudukkan dalam Pasal 289 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Dalam pasal tersebut jika dicermati dengan baik terdapat pula unsur “memaksa” yang menjadi batasan dalam pendifinisian perbuatan cabul. Jika kita memberikan narasi kontra yang sama dengan peraturan menteri yang saat ini diperdebatkan, maka akan ditemukan penafsiran yang ambigu pula pada undang-undang ini. Unsur kata memaksa akan dapat didefinisikan sebagai pelegalan tindakan cabul apabila tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan tersebut. Namun, unsur memaksa merupakan hal yang sangat penting dalam mendefinisikan suatu perbuatan dapat dikatakan cabul dan melanggar kesusilaan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melakukan pencabutan dan/atau revisi terhadap peraturan tersebut hanya karena alasan interpretasi yang berbeda dengan domainnya.
Aturan tentang seks bebas dan perzinahan diperlukan
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moralitas dan kesopanan. Ada banyak nilai-nilai luhur bangsa yang saat ini berkembang menjadi kebiasaan dan norma di masyarakat. Sebagai penduduk beragama Islam yang dibesarkan dengan norma dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tentu saja saya sangat menolak pelegalan seks bebas dan perzinahan dengan cara apapun. Begitu pula menurut saya sebagian besar masyarakat Indonesia tanpa melihat identitas agama dan kepercayaannya. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia memiliki norma yang berkembang di masyarakat yang secara tidak langsung hadir menjadi hukum yang hidup.
Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan bentuk sistem hukum yang berkembang di Indonesia yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum eropa kontinental salah satunya, diperlukan adanya aturan tertulis dalam hal ini perundang-undangan yang sesuai dengan nilai dan norma yang lahir dan berkembang dari bangsa Indonesia itu sendiri. Seks bebas dan perzinahan adalah satu diantara sekian banyak hal yang perlu untuk segera dikaji aturan perundang-undangannya. Karena kedua hal tersebut tentu saja melanggar nilai dan norma yang hadir sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Berdasarkan apa yang kemudian saya pahami dan merupakan poin utama dari tulisan ini, penemuan hukum tentang aturan mengenai seks bebas dan perzinahanlah yang diperlukan. Bukan perdebatan tentang suatu frasa yang sudah sangat jelas merupakan unsur yang memberikan batasan pendefinisian dari suatu pasal.
Karena saat ruang-ruang publik dipenuhi dengan perdebatan bahkan cacian terhadap mereka yang berbeda pendapat, disaat yang sama pula ada orang-orang yang sedang berjuang melawan dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan seksual yang mereka alami.