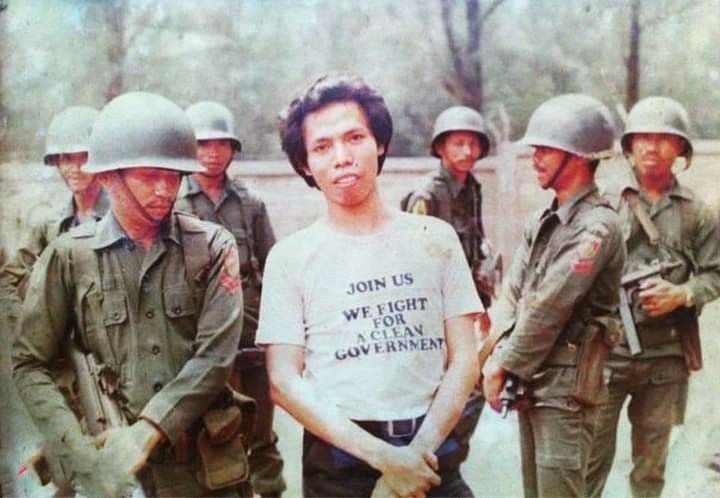Moh. Supri
(Kordinator Dewan Pers LPMH-UH)
Diceriterakan dalam sebuah prolog, seorang Petapa dalam perenungan panjang membawanya pada pencerahan tentang makna kehadiran manusia dalam kehidupan. Dalam hati ia mulai bertanya, apa gunanya segala khazanah pengetahuan bila hanya untuk kemanfaatan pribadinya semata. “Wahai bintang agung! Apalah arti kebahagiaanmu seandainya tak ada mereka yang kau sinari,” ia bermonolog. Terbawa pada tekad kuat mengenai makna kehidupan, Petapa meninggalkan gua persemediannya, turun gunung menemui manusia.
Demikian prolog dalam untaian karya fenomenal Friedrich Nietzsche “Thus Spake Zarathustra”, Sabda Zarathustra. Kurang lebih dalam kisah tersebut, Nietzche berupaya menggugah satu nilai yang fundamental pada interaksi individu terhadap kehidupan bermasyarakat. Sebuah langkah penyempurnaan kemanusiaan yang disebutnya sebagai “Adi manusia”. Substansinya, adalah seberapa besar sumbangsih individu dalam menciptakan kebaikan, tak semata pada kemanfaatan pribadi.
Garis batas keberpihakan adalah hal yang seringkali dipertanyakan dalam menanggapi gejolak sosial. Respon tiap-tiap individu terhadap fenomena sosial umumnya bervariasi. Argumentasi bisa saja saling bersilangan, berbuntut pada perdebatan panjang mengenai cara pandang. Namun pada kesimpulannya, pendapat dan argumentasi demikian bermuara pada dua pilihan, ya atau tidak. Pendikotomian membuat tegas garis keberpihakan seseorang, membawa individu pada dua sikap; sinisme atau simpatik.
Reaksi terhadap fenomena sosial, aktor, simpatisan dan partisipan dilekatkan pada dua fenomena permanen, yakni pencarian identitas dan pengakuan dari pihak lain. Demikian menurut sosiolog kebangsaan Italia, Alessandro Pizzorno. Interpretasi yang berkaitan dengan logika tindakan dan ikut andilnya individu dalam suatu fenomena sosial bukanlah hal yang berkonotasi negatif. Hal ini perlu dipandang sebagai bentuk kebebasan individu dalam menentukan sikap, bukan sebagai ajang penghakiman seperti fenomena pencitraan yang marak dipraktikkan akhir-akhir ini.
Harus diakui, tentang posisi keberpihakan, ketegasan mengambil sikap dalam menanggapi fenomena sosial, telah terbangun stigma di dalamnya. Jurus andalan yang diterapkan oleh aktor politik di atas papan catur perpolitikan di Indonesia bernama pencitraan. Fenomena kongkret dapat diamati akibat dari pesta demokrasi pada pemilihan presiden lalu. Presiden Joko Widodo kerap disebut sebagai tokoh penemu “Blusukan”. Sebuah langkah mendekatkan diri terhadap masyarakat, sosok pemimpin yang merakyat adalah sosok yang menjadi idaman dalam mimpi panjang bangsa ini. Keefektifan langkah blusukan tersebut terbukti dengan terpilihnya sosok Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke tujuh.
Walaupun demikian, bias dari blusukan mulai nampak pada tindakan-tindakan pejabat Negara dan respon masyarakat. Praktek serupa seringkali diterapkan untuk meraih simpati warga, bahkan batasan mengenai kewajiban pejabat Negara untuk mengayomi masyarakat semakin samar. Tak ada akting blusukan yang terjadi jika tak tertangkap lensa kamera jurnalis. Akibatnya, kepercayaan masyarakat bukan semakin baik, lebih dari itu, ada semacam kesan yang melekat, bahwa segala tindakan pejabat publik yang diliput media memiliki agenda tersembunyi di belakangnya. Tak ada lagi tindakan yang benar-benar murni untuk kesejahteraaan rakyat. Ada dalih pencitraan yang melekat pada pola pikir masyarakat, tak ada tindakan yang benar-benar tulus untuk membangun bangsa.
Demikian halnya dalam praktek kehidupan kemahasiswaan. Ada dua sikap yang terbangun jelas saat menanggapi gejolak sosial. Sinisme atau simpatik. Sinisme mengartikan sikap dan tindakan aktor dalam gerakan sosial sebagai tindakan yang sia-sia, memandang rendah dan berprasangka buruk bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Simpatik adalah lawan dari sinisme, pihak-pihak yang berpandangan bahwa tindakan demikian merupakan sebuah bentuk dukungan yang bermuara pada kepentingan bersama. Bagi yang gemar mengamati hiruk-pikuk kampus, tentu menemukan kedua enigma tersebut. Tak mengherankan ruang-ruang diskusi lepas terkait wacana sosial dan kemasyarakatan amat sulit ditemui di lingkup kampus. Padahal notabenenya peserta didik perguruan tinggi menanggung “utang” pengabdian kepada masyarakat.
Umumnya tak hanya peserta didik, pendidik bahkan masyarakat pun mulai terserang sindrom yang sama. Hal ikhwal demokrasi dan kebebasan berpendapat menjadi persoalan besar dewasa ini. Aturan mengenai tata tertib kehidupan kampus tak diimbangi dengan hak-hak mahasiswa dalam menuntut haknya. Pengelola dan pejabat kampus berbekal instrumen regulasi, cenderung sepihak dalam menerapkan kebijakan yang menimbulkan bias di kalangan mahasiswa. Gema dan riak-riak penolakan dianggap sebagai langkah pembangkangan, dan secepat mungkin harus diamputasi. Di lingkup masyarakt pun tak kalah memprihatinkan. Demonstrasi menjadi kesan buruk, dianggap mengganggu stabilitas lalu lintas dan perekonomian lokal. Akrab di telinga para demonstran kata-kata hujatan, ungkapan kejijikan bahkan terkadang massa aksi harus berdepan dengan amukan warga.
Lalu bagaimana halnya bagi pihak yang bereaksi di luar daripada sikap sinisme dan simpatik? Golongan yang selalu memposisikan diri sebagai “orang tengah” dengan menawarkan langkah solutif, hasil dari pertarungan kedua kubu?
Ulasan menarik di sampaikan Goenawan Mohammad dalam catatan pinggirnya edisi 9 Desember 1978, Ekstrim dan Moderat. Goenawan menglasifikasikan pihak tersebut sebagai “orang-orang tanpa warna.” Meski baginya hal tersebut tidak salah, melainkan pengejawantahan dari keberanian untuk berpikir bebas, yang juga merupakan sebuah pilihan. Justifikasi mengenai warna, keberpihakan, demarkasi adalah tanggungan bagi konsekuennya. Sebagaimana pandangan Jean P Sartre bahwa manusia merealisasikan dirinya dalam kebebasan pilihannya. Berani memilih berarti siap untuk dipilih. Dipilih sebagai lawan ataupun kawan. Lebih baik, ketimbang dianggap tak pernah ada dalam lingkaran dan sirkulasi sosial.
Mengenai rumusan tindakan dan garis keberpihakan, Ali bin Abi Thalib Ra punya sebuah petuah yang bijak. “Kenalilah kebenaran, maka pastilah engkau akan mengenal, siapakah yang berada pada pihak yang benar”.